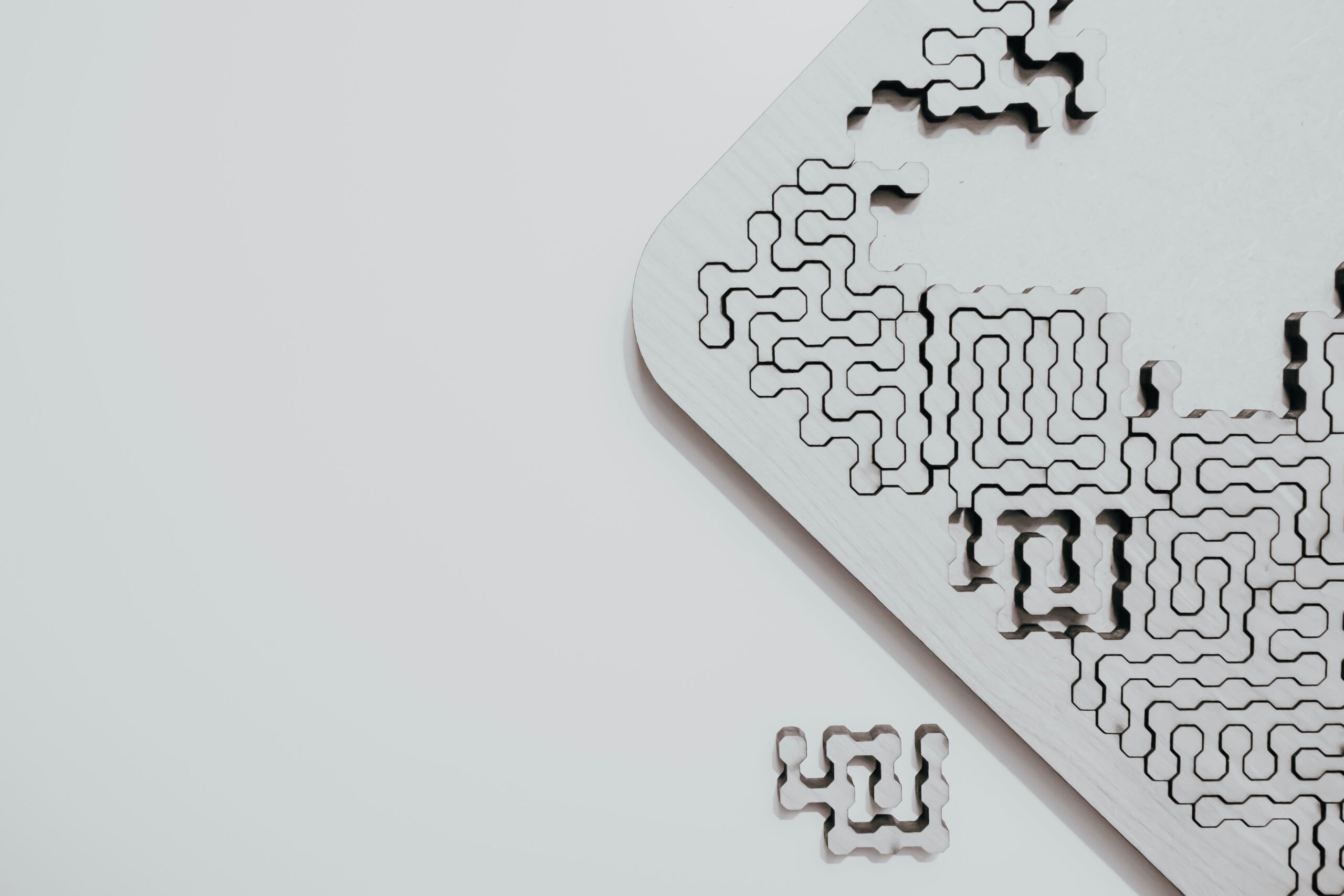Pada tahun 2020 lewat Digital Civility Index (DCI) Microsoft menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan warganet paling tidak sopan. Tepatnya urutan ke-29 dari 32 negara, yang berarti merupakan ranking terendah di Asia Tenggara. Di sisi lain, jauh sebelum dunia maya menuai popularitasnya, banyak yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia justru dikenal ramah dan baik hati. Aertinya terdapat dua kontradiksi bagaimana masyarakat Indonesi dipandang oleh dunia. Terlepas dari paradoks tersebut, nyatanya label tidak sopan atau ramah disematkan dalam kata “masyarakat Indonesia” yang seolah-olah menggambarkan populasi secara keseluruhan, atau setidaknya menunjukkan bahwa mayoritas rakyat di negara kita berperilaku demikian. Lantas pertanyaannya, hal apa yang membuat kebanyakan anggota di suatu kelompok memiliki karakter, perilaku dan cara berpikir hampir serupa?
Raymond Cattel, seorang teoritikus kepribadian membangun sebuah postulat bahwa pada dasarnya kelompok memiliki kepribadian yang disebut sebagai sintalitas (syntality). Sintalitas terbangun akibat adanya dinamika interaksi antar anggota kelompok. Artinya, perilaku dan karakteristik individu dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung akan membentuk sifat serta perilaku populasi. Maka, bukan tidak mungkin kepribadian kelompok akan semakin kuat dengan lahirnya individu yang dididik dan ditumbuhkan dengan sistem sosial dan pola perilaku yang ada di kelompok tersebut. Dengan kata lain, ada hubungan resiprokal atau saling mempengaruhi antara sintalitas populasi dengan kepribadian anggota di dalamnya.
Interaksi antara individu dengan kelompok dijelaskan secara holistik oleh Bronfenbrenner melalui model bioekologi. Ia membangun sebuah argumen bahwa ketika seorang individu lahir sebagai salah satu anggota masyarakat, maka pertumbuhan personalnya akan dipengaruhi oleh berbagai struktur dan sistem sosial yang ada. Misalnya, ketika seorang anak lahir di suatu negara, maka proses perkembangannya akan turut dideterminasi oleh berbagai dimensi sosial mulai dari kondisi keluarga, sekolah, sistem politik, sistem pendidikan atau kesehatan, keadaan ekonomi, nilai dan budaya negara sampai dengan berbagai kejadian historis yang melingkupi anak tersebut ataupun negara tempat ia berada.
Di sisi lain, Carl Jung mencoba memberikan pandangan yang lebih radikal bahwa seluruh manusia memiliki fondasi karakter psikologis yang sama. Lewat proposisinya Jung tidak membicarakan dinamika kelompok, namun mengatakan setiap entitas inidividu lahir dengan membawa ketidaksadaran kolektif (collective unconscious), yaitu bentuk pikiran atau memori yang tidak disadari yang berakar dari leluhur manusia. Ketidaksadaran kolektif termanifestasi melalui berbagai kesamaan sikap dan perilaku manusia mengenai banyak hal. Misalnya saja, Jung mengatakan bahwa konsep Ketuhanan merupakan sesuatu yang diturunkan secara tidak sadar sehingga setiap generasi manusia akan selalu meyakini eksistensi Tuhan. Selain itu, bentuk lain dari ketidaksadaran kolektif adalah manusia bisa memahami ekspresi emosi lewat wajah sejak dini padahal tidak pernah belajar sebelumnya; atau bagaimana orangtua yang secara “instingtif” menyayangi anaknya.
Terlepas dari konsepnya yang kontorversial, Jung berpendapat bahwa banyak perilaku manusia didasari oleh dorongan ketidaksadaran kolektif yang diturunkan dari nenek moyang. Hanya saja kontennya bisa berbeda diakibatkan oleh nilai-nilai budaya. Misalnya saja secara mendasar manusia mempercayai Tuhan, namun agama dan gambaran mengenai Tuhannya berbeda. Bentuk lain misalnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk damai, namun ada beberapa kelompok yang caranya adalah dengan memulai perang karena menurutnya hal tersebut akan mempertahankan kedamaian diri dan populasinya. Tidak hanya lewat bentuk perilaku, beberapa konten ketidaksadaran kolektif pun dapat muncul lewat mimpi, fantasi atau berbagai ide yang tiba-tiba muncul.
Jelas bahwa konstruk ketidaksadaran kolektif dari Jung menuai kritik tajam karena tidak memenuhi kaidah ilmiah yang Karl Popper sebut sebagai falsifiability. Di sisi lain, banyak pihak menyayangkan bahwa konsep yang dibangun lewat pendekatan sosial-kepribadian dari Cattel ataupun model bioekologi Bronfenbrenner masih dianggap sulit untuk divalidasi secara empiris. Menariknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad-21 membawa para peneliti menuju pemahaman mengenai relasi antara mental individu dengan kondisi lingkungannya secara lebih objektif. Salah satunya dengan memahami aspek psikologis manusia melalui kacamata biologi molekuler dan genetika.
Tedapat sebuah tulisan menarik dalam esay ilmiah Transgenerational Epigenetics of Traumatic Stress yang ditulis oleh Jawaid, Roszkowski dan Mansuy. Mereka melakukan kajian terhadap berbagai studi dan bermuara pada satu kesimpulan bahwa stres traumatis yang dialami oleh seseorang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya tanpa individu dalam generasi tersebut mengalami kondisi serupa dikarenakan adanya kondisi epigenetik. Epigenetik merupakan perubahan pada ekspresi atau aktivitas gen seseorang yang diakibatkan oleh banyak faktor termasuk lingkungan, gaya hidup, usia, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perilaku, kebiasaan dan interaksi yang kita bangun dengan dunia luar dapat mempengaruhi keadaan diri kita sampai pada level selular. Maka tidak heran kondisi yang individu alami dapat diturunkan karena hal tersebut telah “terekam” pada tataran genetik.
Seorang Profesor Neuropsikitari asal Amerika, Rachel Yehuda mencoba membuktikan hipotesis mengenai trauma yang diwariskan. Ia meneliti keturunan-keturunan dari penyintas holokaus pada masa NAZI dan menemukan bahwa kondisi trauma yang dialami para penyintas ternyata dapat meningkatkan resiko munculnya masalah psikologis, kerentanan terhadap gangguan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD; stres pasca trauma) dan menyebabkan ketidakseimbangan hormon kortisol (hormon yang berkaitan erat dengan stres) pada anak cucu mereka. Dalam salah satu penelitiannya Yehuda mengatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh berbagai perubahan aktivitas gen, seperti gen FKBP5 yang seringkali diasosiasikan dengan kemunculan depresi.
Tidak hanya Yehuda, para peneliti lain dari berbagai belahan dunia pun menemukan hasil yang serupa. Mereka membuka fakta bahwa berbagai kekacauan seperti Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang Kamboja, Perang Rwanda dan perang Bosnia-Serbia telah menggariskan luka psikologis tidak hanya bagi para penyintas, namun juga ditransmisikan sampai generasi-generasi di bawahnya. Sebagai implikasinya, kondisi demikian membuat para anak cucu mereka memiliki potensi yang lebih besar dalam memunculkan kecemasan, depresi, gangguan somatik, bahkan sampai masalah perkembangan emosi dan perilaku sosial seperti menunjukkan sikap permusuhan. Maka tak ayal berbagai ancaman sosial yang dialami seorang individu dapat menjadi sumber kemunculan masalah kesehatan mental antar generasi.
Guna memperkuat konstruksi ilmiahnya, pengujian hipotesis mengenai “memori warisan” juga dilakukan dalam ruang eksperimen dengan kontrol yang ketat. Dias dan Ressler melakukan studi transgenerasi dengan menggunakan tikus. Mereka mengkondisikan agar seekor tikus memiliki ketakutan terhadap sebuah bau (asetofenon) sebelum masa kawinnya. Menariknya, dua generasi setelahnya memiliki ketakutan yang sama terhadap asetofenon walaupun mereka tidak pernah dipaparkan atau dikondisikan untuk takut dengan bau tersebut sebelumnya. Para peneliti menemukan bahwa terjadi perubahan neuroanatomi yang disebut Olfr151 yang membuat para tikus sensitif terhadap bau. Tidak hanya itu, mereka pun mendapatkan beberapa alterasi pada aspek-aspek genetik lainnya. Melalui studi tersebut Dias dan Ressler menyimpulkan bahwa informasi yang individu peroleh dari lingkungan ternyata dapat diturunkan antar generasi dalam level perilaku, neuroanatomi dan epigenetik.
Berbagai studi mengenai transgenerasi membuahkan satu pertanyaan baru dari para peneliti itu sendiri. Sampai berapa generasikah suatu kondisi akan persisten diturunkan? Sayangnya belum ada jawaban pasti mengenai hal tersebut walaupun ada beberapa riset yang mengatakan bahwa mereka menemukan hasil transmisi dari leluhur masih tetap eksis di generasi ketiga. Sementara itu pandangan evolusi meyakini sebenarnya “memori” nenek moyang akan terus ditransmisikan pada setiap keturunan. Para ahli biologi evolusi pun menekankan proses pengalihan memori tidak selalu berarti buruk, namun juga dapat berdampak positif bagi adaptasi generasi berikutnya. Tentunya hal tersebut tergantung jenis kondisi atau kemampuan apa yang diturunkan.
Bukan tanpa alasan kaum evolusi mengkalim kemungkinan transgenerasi epigenetik terus menerus diwariskan. Pasalnya terdapat sebuah temuan menarik mengenai Mitochondrial Eve (Mitokondria Hawa), yaitu nenek moyang perempuan pertama dari seluruh umat manusia. Dalam konteks selular, mitokondria merupakan bagian dari sel yang berfungsi memproduksi energi. Pada mitokondria terdapat sebuah DNA yang berasal hanya dari ibu. Dengan kata lain seorang anak mendapatkan DNA mitokondria dari ibunya, lalu ibu tersebut mendapatkan dari ibunya lagi, terus seperti itu. Sampai akhirnya, saat ditelusuri semua manusia memiliki DNA mitokondria yang sama dan berasal dari sesosok makhluk di Afrika yang hidup sekitar 250.000 tahun lalu yang peneliti sebut sebagai Eve. Oleh karena itu, secara biologis Eve dianggap sebagai ibu dari seluruh manusia. Dengan fakta bahwa manusia berbagi DNA mitokondria yang sama, maka bukan hal yang aneh jika banyak akademisi berasumsi mengenai kemungkinan proses pewarisan memori terus berlangsung dalam rentang generasi yang panjang.
Berbagai temuan empiris mengenai memori warisan bukan hadir tanpa perdebatan. Nyatanya banyak pula akademisi dan peneliti yang mengungkapkan skeptismenya terhadap hipotesis dan temuan-temuan tersebut. Beberapa menegasikan dengan cara memberikan catatan mengenai relevansi metode yang digunakan. Mereka menganggap bahwa limitasi pemahaman mekanisme genetik, model eksperimen dan obeservasi yang dilakukan menjadi penghambat untuk membuktikan temuan secara valid. Belum lagi ada anggapan bahwa bisa jadi sifat atau perilaku yang diwariskan itu justru lebih kuat berasal dari pola asuh, pendidikan ataupun budaya yang ditanamkan oleh orangtua dan leluhurnya sejak seorang individu lahir. Selain itu, para tokoh indeterminisme meyakini jika segala takdir individu telah ditentukan oleh kondisi biologis dan genetik maka manusia akan kehilangan jati dirinya sebagai manusia karena tidak lagi memiliki kehendak bebas (free will). Kondisi demikian menjadi tembok yang memunculkan keraguan bagi sebagian orang mengenai apakah transgenerasi genetik merupakan sesuatu yang nyata atau tidak.
Terlepas dari ragam teori, temuan atau kritik yang ada mari kita kembali ke kondisi masyarakat dan warganet Indonesia. Berbagai temuan mengenai memori warisan telah megundang sebuah pertanyaan menggelitik. Apakah karakter, buah pikir dan perilaku manusia Indonesia yang kita lihat sekarang ada hubungannya dengan transgenerasi genetik dari kejadian masa lalu bangsa ini? Masa lalu mengenai jejak panjang sejarah penjajahan selama 350 tahun yang bukan tidak mungkin meninggalkan luka traumatis bagi para nenek moyang. Bagaimanapun penelitian transgenerasi genetik belum sampai pada jawaban dan kesimpulan atas pertanyaan tersebut. Lantas, bagaimana dengan kita? Apakah memori warisan dari nenek moyang memberikan andil terhadap perilaku dan kesehatan psikologis kita saat ini? Sepertinya, kondisi tersebut belum dapat dipastikan dengan seksama. Hal yang jelas adalah kondisi genetik memiliki potensi untuk berubah tergantung dari perilaku, gaya hidup, keputusan dan cara berpikir individu. Dengan demikian, muncul sebuah pertanyaan asumtif, jangan-jangan perilaku dan kebiasaan baik kita akan mengubah aktivitas gen menjadi lebih baik, kemudian hal tersebut akan diwariskan pada keturunan selanjutnya sehingga melahirkan generasi-generasi manusia yang lebih baik lagi?
Ashiabi, G. S., & O’Neal, K. K. (2015). Child Social Development in Context. SAGE Open, 5(2), 215824401559084. https://doi.org/10.1177/2158244015590840
Cattell, R. B. (1948). Concepts and methods in the measurement of group syntality. Psychological Review, 55(1), 48–63. https://doi.org/10.1037/h0055921
Dias, B. G., & Ressler, K. J. (2013). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17(1), 89–96. https://doi.org/10.1038/nn.3594
Hewitt, A. (2017). Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibility: Insights from Genetics and Neuroscience. The New Bioethics, 23(2), 188–190. https://doi.org/10.1080/20502877.2017.1345093
Ho, W. C., Li, D., Zhu, Q., & Zhang, J. (2020). Phenotypic plasticity as a long-term memory easing readaptations to ancestral environments. Science Advances, 6(21), eaba3388. https://doi.org/10.1126/sciadv.aba3388
Horsthemke, B. (2018). A critical view on transgenerational epigenetic inheritance in humans. Nature Communications, 9(1). https://doi.org/10.1038/s41467-018-05445-5
Jawaid, A., Roszkowski, M., & Mansuy, I. M. (2018). Transgenerational Epigenetics of Traumatic Stress. Progress in Molecular Biology and Translational Science, 273–298. https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2018.03.003
Jung, C. (2021). The Archetypes and the Collective Unconscious [E-book]. Important Books (1 Dec. 2013).
Klinger-König, J., Hertel, J., van der Auwera, S., Frenzel, S., Pfeiffer, L., Waldenberger, M., Golchert, J., Teumer, A., Nauck, M., Homuth, G., Völzke, H., & Grabe, H. J. (2019). Methylation of the FKBP5 gene in association with FKBP5 genotypes, childhood maltreatment and depression. Neuropsychopharmacology, 44(5), 930–938. https://doi.org/10.1038/s41386-019-0319-6
Manosevitz, M. L. J. L. G. H. C. S. C. (2021). Introduction to Theories of Personality by Calvin S. Hall (1985–03-07). Wiley; 1 edition (1985–03-07).
“Mitochondrial Eve”: Mother of all humans lived 200,000 years ago. (2010, August 7). ScienceDaily. https://www.sciencedaily.com/releases/2010/08/100817122405.htm
The Great Courses. (2020, November 20). Mitochondrial Eve: The Mother of All Human Beings. The Great Courses Daily. https://www.thegreatcoursesdaily.com/mitochondrial-eve-the-mother-of-all-human-beings/
Weinhold, B. (2006). Epigenetics: The Science of Change. Environmental Health Perspectives, 114(3). https://doi.org/10.1289/ehp.114-a160
WhatIsEpigenetics.com. (2018, March 15). Epigenetics: Fundamentals, History, and Examples. What Is Epigenetics? https://www.whatisepigenetics.com/fundamentals/
Xavier, M. J., Roman, S. D., Aitken, R. J., & Nixon, B. (2019). Transgenerational inheritance: how impacts to the epigenetic and genetic information of parents affect offspring health. Human Reproduction Update, 25(5), 519–541. https://doi.org/10.1093/humupd/dmz017
Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., Bader, H. N., Klengel, T., Holsboer, F., & Binder, E. B. (2016). Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation. Biological Psychiatry, 80(5), 372–380. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2015.08.005